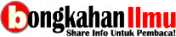Surat Terbuka IRT Kepada Seluruh Parlemen Di Aceh
Cut Bang Din Minimi Tiba di Desa Limpoek, kabupaten Aceh Besar Darussalam


Pasukan Brimob (Kiri) dan Din Minimi (Kanan)
Mutia: Tragedi 5 Mei 2015 di Limpoek kembali mengatarkan saya pada tahun-tahun di mana Aceh dalam kondisi perang
“Buka! Buka pintunya!” kata seseorang sambil menggedor dan menendang pintu garasi rumah kami, “Cepat dibuka, keluar semua!” sang tamu mengusir kami ke luar rumah !
Kepada Gubernur Aceh
Kepada Dewan Perwakilan Aceh
Kepada seluruh pemangku kepentingan di Aceh
Berikut kabar yang saya tulis demi situasi yang telah terjadi di Desa Limpoek, tempat saya bernaung saat ini.
Perlu diketahui, jika bukan tentang anak negeri, jika bukan karena kisah masa usang yang belum usai, jika bukan tentang pengkhianatan dan kebodohan yang terus menerus kita belai, sungguh!
Sampai detik ini saya belum bersedia menggerakkan jari jemari saya untuk merangkai kata sehingga menjadi kalimat yang bisa dibaca dan disebarkan ke seluruh penjuru negeri esok atau lusa nanti.
Sebelum perjanjian damai terajut di bumi Serambi Mekah, Desa Limpoek, kabupaten Aceh Besar telah dinobatkan sebagai salah satu daerah yang masuk ke dalam zona merah oleh aparat keamanan Negara Republik Indonesia.
Di sini pasukan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ketika itu berdiam diri dan berleha-leha. Di Desa ini juga Universitas Syiah Kuala berdiri tegak kekar menghadang angkasa raya. Ilmu dan pemberontakan hanya berjarak sedepa.
Di awal tahun 2007, ketika saya mulai membangun rumah di Desa Limpoek, bermacam ungkap menghinggapi kuping saya.
”Kenapa harus tinggal di Limpoek, itu daerah rawan?” Kalimat tersebut terus saja meluncur dari mulut siapa saja yang mengenal Desa Limpoek, hingga beberapa tahun kemudian, Limpoek mampu membuktikan dirinya kalau ‘dia’ bukanlah desa tempat bernaungnya para setan, jin dan dedemit sehingga patut untuk ditakuti dan dijauhi.
Menjamurnya rumah kontrakan, kos-kosan, penginapan dan perumahan di Limpoek menjadi indikator terbesar kalau Limpoek bukan lagi sumur tua tempat si tukang sihir mencari ilmu kebal.
Walau insiden 5 Mei 2015 muncul secara tak terduga, bagi saya Limpoek tetap saja desa bersahaja.
Lebih kurang dua ratusan pasukan Brimob, dari Reskrim Polda Aceh dan Reskrim Polresta Banda Aceh menyebar di seluruh sudut Desa Limpoek.
Mereka menghitam menyerupai dedaun ketika malam. Mereka menyebar dengan suara gaduh yang siap sedia mengantarkan para penderita jantung kronis untuk segera berlabuh ke Unit Gawat Darurat.
“Buka! Buka pintunya!” kata seseorang sambil menggedor dan menendang pintu garasi rumah kami, 5 Mei 2015.
Mereka berteriak suka-suka. Kebetulan saya yang sedikit alergi dengan tetamu itu menyambut gedoran itu dengan kalimat,”Bek gabuk-gabuk, jak u rumoeh gop beuna etika bacut(Jangan ribut, bertamu itu harus punya etika-red).”
“Cepat dibuka, keluar semua!” sang tamu mengusir kami ke luar rumah.
Mendengar arogansi yang tak terkendali, saya pun bertanya dengan nada yang lumayan tinggi.
“Ada apa ini, apa tujuan kalian?”.
“Kami sedang mencari anak buahnya Din Minimi yang lari ke arah rumah ibu.” Dalam gaduh mereka menjelaskan tujuannya mengerebek rumah kami.
Dengan santai lagi-lagi saya menyela,”Ooo, Cut Bang Din Minimi Cs kateuka u Banda rupajih. Ngen Din Minimi sidro gabuk ureung ban saboh nanggroe.”(Ooo, Cut Bang Din Minimi Cs sudah berada di Banda Aceh rupanya. Din Minimi saja bisa rusush satu negeri-red).
Tragedi 5 Mei 2015 di Limpoek kembali mengatarkan saya pada tahun-tahun di mana Aceh dalam kondisi perang. Masih melekat dalam ingatan saya, terakhir saya kedatangan tetamu serupa pada bulan Januari 2003.
Mereka menggedor rumah kontrakan kami di Desa Lamnyong Banda Aceh. Mereka datang dengan cara yang sama, namun tujuan yang berbeda. Ketika itu mereka mencari Cut Farah, ketua dari sebuah organisasi massa Perempuan Merdeka.
Sekarang tetamu itu datang untuk mencari pasukan Din Minimi yang dalam penglihatan saya hanya seorang lelaki begal yang membutuhkan perhatian dan belaian dari pemerintah maupun dari organisasi yang pernah mengajarinya bagaimana mengokang AK 47.
Din Minimi CS bukanlah gerombolan yang patut untuk dibesar-besarkan, mereka hanya komplotan preman tak ubahnya begal di DKI Jakarta, bajing loncat di Palembang, geng motor di Batam dan preman-preman lainnya yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Mereka hanya butuh kasih sayang dan perhatian dari pemerintah dan para panglimanya. Inginnya mereka sangatlah sederhana, “Adanya keadilan.”
Sama juga dengan inginnya saya dan masyarakat lainnya. Kata-kata sederhana yang sering diabaikan. Bahkan sudah 10 tahun damai berlalu, realisasi kata-kata “keadilan” masih jauh dari harapan.
Beberapa teman CSO sering menyatakan bahwa kasus Din Minimi Cs adalah salah satu indikator kalau proses reintegrasi tidak berhasil, positif peace belum lahir.
Analisa demi analisa terus saja digulirkan, ujung-ujungnya Jakarta menjadi kambinghitam, mencari-cari kesalahan orang lain daripada memperbaiki diri sudah menjadi tabiat orang-orang kalah.
Padahal Aceh bisa melakukan apapun yang diinginkannya, semua kembali kepada niat dan kemampuan para pemimpinnya, baik eksekutif maupun legislative.
Demikian juga dengan kasus Din Minimi Cs, andai Gubernur Aceh dan panglima tertinggi KPA berjiwa besar dan bersedia memanggil Din Minimi Cs untuk duduk dan berbicara dari hati ke hati (komunikasi persuasif) seperti yang pernah dilakukan oleh Gubernur Irwandi Yusuf terhadap komplotan serupa pada tahun 2008, maka Din Minimi Cs tidak akan jatuh ke dalam genggaman para pihak yang hanya memanfaatkan rasa haus dan lapar Din Minimi Cs untuk popularitasnya semata.
Ya, para pihak yang ingin menjadikan Aceh sebagai lahan tempat mencari pangkat dan mengumpulkan pundi-pundi rupiah.
Andai jauh-jauh hari para petinggi negeri (gubernur, wali dan ketua KPA) bisa bersikap bijak dalam menyelesaikan kasus ini, maka Bang Din Minimi Cs tidak akan sampai ke Limpoek, cukup Nisam sebagai destinasi akhir mereka.
Demikian dan terimakasih.
Penulis adalah Cut Meutia,
Ibu Rumah Tangga tinggal di Limpoek